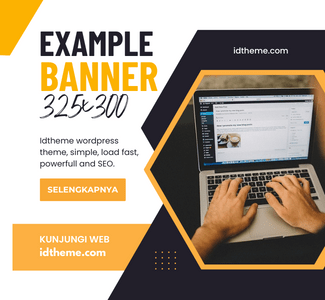Penulis: Dr. Bambang S. Irianto, Dosen FH UPN “Veteran” Jatim
Surabaya,Jurnal Hukum Indonesia.–
Pendahuluan;
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan abolisi dan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abolisi dan amnesti merupakan bentuk grasi kolektif yang bertujuan menjaga stabilitas negara, memperkuat rekonsiliasi nasional, atau merespons situasi politik dan sosial yang luar biasa. Namun demikian, pelaksanaannya sering kali menimbulkan polemik, terutama ketika diberikan kepada tokoh politik yang tengah terjerat proses hukum. Polemik tersebut kembali mencuat dalam dua kasus yang belakangan menarik perhatian publik, yakni pemberian abolisi kepada Tom Lembong, mantan pejabat publik yang terseret dalam isu hukum tertentu, serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto, politisi senior dan Sekjen partai politik besar yang tengah menghadapi dugaan menghalangi proses hukum (obstruction of justice). Kedua keputusan ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana pemberian abolisi dan amnesti dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, dan sejauh mana justru ditentukan oleh kepentingan politik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana instrumen hukum publik dapat dibingkai ulang dalam dinamika kekuasaan, sehingga membuka ruang diskusi tentang etika kekuasaan, supremasi hukum, serta akuntabilitas pejabat tinggi negara dalam menjalankan kewenangan istimewanya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam dimensi politik di balik pemberian abolisi dan amnesti dalam kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.
Selain menyoroti aspek hukum dan konstitusionalitas pemberian abolisi dan amnesti, tulisan ini juga akan melihat bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh publik, terutama dalam konteks kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan integritas lembaga kepresidenan. Ketika tokoh politik yang sedang disorot publik justru mendapatkan pengampunan hukum dari Presiden, muncul kecurigaan bahwa kebijakan tersebut bukan semata-mata lahir dari pertimbangan keadilan, melainkan lebih karena kedekatan politik, loyalitas, atau manuver kekuasaan. Kondisi ini dapat mencederai prinsip _equality before the law_, di mana setiap warga negara seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan politik, atau afiliasi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali sejauh mana kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi dan amnesti memiliki mekanisme kontrol yang efektif, baik secara hukum maupun etika, agar tidak disalahgunakan atau dijadikan alat kompromi politik. Dengan mengambil dua kasus aktualTom Lembong dan Hasto Kristiyanto maka tulisan ini berupaya menguraikan persoalan-persoalan normatif dan praktis yang menyertai pemberian abolisi dan amnesti, serta mencoba menjawab pertanyaan mendasar: apakah hukum masih menjadi panglima, atau telah tergantikan oleh kompromi dan kalkulasi kekuasaan ?
Amnesti dan abolisi merupakan bentuk pengampunan hukum yang sifatnya kolektif. Amnesti diberikan untuk menghapus seluruh akibat pidana terhadap suatu tindak pidana (biasanya terkait politik), termasuk menghapus putusan pengadilan dan pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, abolisi lebih ditujukan untuk menghentikan proses hukum terhadap individu atau kelompok tertentu, sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kedua kebijakan ini harus melalui proses pertimbangan politik di DPR, namun tidak secara eksplisit mengharuskan adanya parameter objektif yang membatasi keputusan Presiden. Di sinilah letak potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika pengampunan hukum diberikan kepada figur yang memiliki afiliasi kuat dengan elite kekuasaan.
Pembahasan;
a. Kedudukan Hukum Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan
Dalam sistem hukum Indonesia, amnesti dan abolisi merupakan dua instrumen pengampunan yang bersumber langsung dari kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
“ … Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat … ”, Amnesti secara umum berarti pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang menghapuskan akibat hukum dari tindak pidana tersebut. Biasanya, amnesti diberikan terhadap pelaku pelanggaran hukum yang bermuatan politis, misalnya pemberontakan atau makar.
Sementara itu, abolisi adalah tindakan menghentikan proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah, sedang, atau akan diperiksa dalam proses pidana. Dalam praktiknya, abolisi bersifat preventif karena menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, walaupun keduanya memiliki dasar hukum yang kuat, pemberian abolisi dan amnesti memunculkan banyak persoalan ketika digunakan terhadap tokoh politik yang sedang menghadapi proses hukum aktif. Ini memunculkan tafsir ganda: apakah tindakan tersebut murni untuk kepentingan nasional atau bagian dari kompromi kekuasaan.
b. Studi Kasus: Abolisi terhadap Tom Lembong
gPemberian abolisi terhadap Thomas Lembong terjadi di tengah ketegangan politik pasca Pemilu dan upaya pemerintah memperkuat stabilitas melalui rekonsiliasi. Tom Lembong merupakan tokoh ekonomi yang memiliki kedekatan dengan kalangan elite politik tertentu, dan sempat disebut-sebut terlibat dalam proses yang berkaitan dengan tindak pidana, namun proses hukum terhadap dirinya dihentikan melalui pemberian abolisi oleh Presiden, dengan dalih kepentingan nasional dan stabilitas pemerintahan. Keputusan ini menimbulkan kritik karena:
Proses pemberian abolisi berlangsung tanpa penjelasan publik yang transparan.
Tidak ada urgensi hukum yang memadai untuk menghentikan proses penyidikan.
Keputusan Presiden berpotensi mencampuri wewenang penegak hukum dan menimbulkan preseden buruk.
Dari sudut pandang hukum tata negara, abolisi terhadap Tom Lembong menimbulkan pertanyaan serius: apakah Presiden masih bertindak dalam koridor hukum, atau sedang menggunakan kewenangannya untuk melindungi kolega politiknya ?
c. Studi Kasus: Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto
Berbeda dengan kasus Tom Lembong, wacana pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto muncul ketika dirinya diperiksa dalam perkara dugaan obstruction of justice dalam kasus korupsi besar. Dalam posisi sebagai Sekretaris Jenderal partai besar, Hasto menjadi figur strategis secara politik sekaligus simbol loyalitas terhadap kekuasaan. Jika benar amnesti diberikan dalam perkara ini, maka terdapat persoalan besar, yaitu:
1. Obstruction of justice bukanlah tindak pidana bermuatan politik, melainkan bagian dari kejahatan hukum biasa yang menghambat penegakan hukum
2. Pemberian amnesti dapat merusak legitimasi aparat penegak hukum, khususnya KPK dan Kejaksaan.
3. Amnesti dalam konteks ini justru memberi kesan bahwa kekuasaan politik dapat membungkam hukum.
Pemberian amnesti kepada tokoh yang sedang diperiksa dalam kasus korupsi, tanpa proses hukum yang tuntas, akan melemahkan prinsip due process of law dan mengaburkan batas antara hak istimewa konstitusional dan penyalahgunaan wewenang.
d. Analisis Politik Hukum
Kedua kasus tersebut mencerminkan bagaimana instrumen konstitusional (amnesti dan abolisi) dapat dijadikan alat kompromi kekuasaan, bukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang adil. Dalam perspektif politik hukum, tindakan Presiden dalam kasus ini memperlihatkan kecenderungan intervensi kekuasaan terhadap hukum, di mana kebijakan negara digunakan untuk kepentingan politis dan stabilitas semu. Secara prinsip, hukum semestinya bersifat impersonal dan universal. Ketika individu tertentu mendapatkan pengampunan hukum karena kedekatan politik, maka keadilan menjadi tumpul ke atas. Publik tidak hanya meragukan komitmen negara terhadap supremasi hukum, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang semestinya netral dan objektif. Oleh karena itu, praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam konteks elite politik harus dikritisi secara tajam. Ketiadaan standar objektif dan mekanisme pengawasan substantif menjadikan kewenangan Presiden terlalu luas dan rentan digunakan untuk tujuan politis. Jika tidak dikoreksi, maka hal ini akan melemahkan prinsip negara hukum dan membuka ruang bagi impunitas yang dilegalkan.
Hasil Yang DIdapat
Dari kajian terhadap kasus pemberian Abolisi terhadap Tom Lembong dan wacana Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, diperoleh beberapa temuan penting yang menggambarkan dinamika antara hukum dan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:
a. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, kewenangan ini bersifat politis karena pelaksanaannya bergantung pada pertimbangan DPR tanpa adanya standar normatif yang baku.
b. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, serta tidak disertai penjelasan hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa abolisi diberikan karena faktor kedekatan politik, bukan berdasarkan alasan objektif atau kebutuhan hukum yang mendesak.
c. Wacana pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto bertentangan dengan prinsip hukum, karena kasus yang menjeratnya merupakan dugaan obstruction of justice, yang tergolong dalam tindak pidana umum, bukan pidana politik. Ini memperlihatkan kecenderungan penyalahgunaan amnesti di luar semangat rekonsiliasi atau pengampunan nasional.
d. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum Negara rentan digunakan sebagai alat negosiasi politik, sehingga melemahkan prinsip equality before the law dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
e. Tidak adanya mekanisme kontrol yang substantif terhadap keputusan Presiden menjadikan amnesti dan abolisi sebagai ruang abu-abu kekuasaan, di mana pertimbangan politis lebih dominan dibanding pertimbangan hukum.
f. Kasus ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari praktik kekuasaan yang transaksional, di mana loyalitas politik dapat “membeli” perlindungan hukum melalui kebijakan pengampunan Negara.
Simpulan:
a. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan wacana amnesti terhadap Hasto
Kristiyanto menunjukkan bahwa instrumen pengampunan Presiden yang diatur
dalam UUD 1945 telah mengalami pergeseran makna dalam praktiknya. Alih-alih
menjadi sarana penyelesaian masalah hukum secara adil dan demi kepentingan
nasional, abolisi dan amnesti dalam kedua kasus tersebut justru menunjukkan
indikasi kuat adanya intervensi politik dalam proses hukum.
b. Kewenangan konstitusional Presiden belum diimbangi dengan mekanisme
akuntabilitas dan transparansi yang memadai.
c. Pemberian pengampunan terhadap tokoh politik yang sedang atau diduga terlibat
tindak pidana melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
d. Penggunaan abolisi dan amnesti dalam konteks yang bermuatan politis
menciptakan preseden buruk dalam praktik ketatanegaraan, di mana hukum
seolah tunduk pada kalkulasi kekuasaan.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa supremasi hukum hanya akan terwujud apabila kewenangan luar biasa seorang Presiden didalam memberikan abolisi maupun amnesti dapat dipraktikkan secara hati-hati, bertanggung jawab dan berbasis kepada kepentingan hukum yang adil, bukan sebagai alat melanggengkan kekuasaan atau melindungi kolega politiknya.
Saran.
a. Perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam undang-undang terkait prosedur pemberian amnesti dan abolisi, termasuk memperjelas batasan penggunaannya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
b. DPR sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap pengampunan Presiden harus lebih kritis dan transparan, serta melibatkan masukan publik dan ahli hukum dalam prosesnya.
c. Lembaga pengawas independen, seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, atau lembaga etik, dapat dilibatkan secara tidak langsung dalam pengawasan terhadap kebijakan pengampunan Negara, khususnya bila menyangkut tokoh politik yang berkuasa.
d. Masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu terus mengawasi dengan upaya mengkritisi kebijakan Negara didalam pemberian abolisi dan amnesti yang berpotensi menyeleweng dari tujuan hukum, dengan harapan agar demokrasi yang ada tidak berubah menjadi oligarki hukum.
e. Penegakan hukum harus tetap dijalankan secara konsisten dan profesional, terlepas dari posisi, jabatan, atau afiliasi politik pelaku. Tidak boleh ada ruang dalam sistem hukum nasional bagi impunitas yang dilegalkan.
Daftar Pustaka
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian Law. Oxford: Oxford University Press.
Jimly Asshiddiqie. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Mahfud MD. (2001). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 tentang Pengujian Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi dan Amnesti.
Kompas.com. (2024, Juni 5). Abolisi untuk Tom Lembong dan polemik publik. Diakses dari https://www.kompas.com
Detik.com. (2024, Juni 10). Wacana Amnesti Hasto Kristiyanto dan Tanggapan Publik. Diakses dari https://www.detik.com