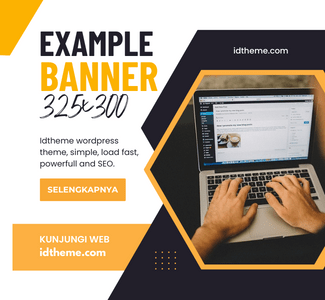Bangkalan, Jurnal Hukum Indonesia
Pertanyaan “Apakah akuntansi bertuhan?” pada awalnya terdengar provokatif. Akuntansi, yang kerap dianggap sekadar teknik pencatatan dan pelaporan keuangan, tiba-tiba ditarik ke ranah spiritual dan transendental. Namun jika ditelaah lebih jauh, akuntansi bukan hanya perangkat teknis, melainkan juga konstruksi sosial yang berakar pada nilai, ideologi, dan kepentingan (Hopwood, 1983; Burchell et al., 1980). Ia bukanlah ilmu netral, tetapi sarat muatan politik, etis, bahkan moral.
Sejarah akuntansi menunjukkan bahwa praktiknya berkembang seiring kebutuhan ekonomi-politik. Pencatatan ganda (double-entry bookkeeping) pada masa Renaisans tidak lahir begitu saja, melainkan terkait erat dengan etika kapitalisme awal (Weber, 1905/2002). Demikian pula, standar akuntansi modern tidak bebas nilai, melainkan hasil kompromi antara kepentingan korporasi, regulator, investor, dan masyarakat (Hines, 1988). Maka, pertanyaan tentang “ketuhanan” dalam akuntansi adalah pertanyaan tentang nilai apa yang melandasi praktik ini: apakah ia dijalankan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kebaikan universal, ataukah hanya demi laba jangka pendek?
Paradigma Akuntansi: Dari Modern ke Postmodern
Akuntansi modern berakar pada paradigma positivistik: objektivitas, kuantifikasi, dan keandalan angka. Namun sejak 1980-an, muncul kritik postmodern yang menyoroti keterbatasan angka dalam merepresentasikan realitas sosial (Tinker, 1985; Cooper & Hopper, 2007). Angka-angka akuntansi seringkali bukan cerminan kebenaran, melainkan “narasi” yang dibentuk oleh pihak berkuasa.
Kritik ini melahirkan berbagai pendekatan alternatif: social and environmental accounting, critical accounting, Islamic accounting, hingga spiritual accounting. Semuanya berupaya menggeser akuntansi dari sekadar alat kapitalisme menuju instrumen akuntabilitas yang lebih etis dan manusiawi.
Konsep “Bertuhan” dalam Akuntansi
Istilah “bertuhan” di sini tidak semata-mata bermakna religius, melainkan mencakup nilai universal yang diyakini tradisi agama dan filsafat moral: kejujuran, keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan pertanggungjawaban transendental. Dalam kerangka Pancasila, misalnya, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi fondasi etis kehidupan berbangsa, termasuk dalam praktik ekonomi dan akuntansi.
Dengan demikian, akuntansi “bertuhan” adalah akuntansi yang:
1. Tidak menipu, tidak memanipulasi angka demi kepentingan sempit.
2. Menjaga keadilan distribusi informasi dan manfaat.
3. Mengakui adanya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada Tuhan, masyarakat, dan lingkungan.
Indikator Akuntansi Bertuhan
1. Kejujuran dan Transparansi
Kejujuran menjadi inti semua agama dan filsafat etika. Dalam akuntansi, ini berarti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi sebenarnya, tidak menyesatkan pengguna laporan. Transparansi adalah perwujudan praktisnya: keterbukaan dalam pengungkapan, tidak ada informasi penting yang disembunyikan.
2. Keadilan Sosial dan Lingkungan
Akuntansi tidak boleh berhenti pada kepentingan investor, melainkan juga harus memperhitungkan dampak sosial dan ekologis. Konsep triple bottom line (Elkington, 1997) menekankan pentingnya memperhitungkan people, planet, profit.
3. Akuntabilitas Transendental
Dalam tradisi Islam, dikenal konsep hisab—bahwa semua amal akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Perspektif serupa ada dalam tradisi Kristen, Hindu, maupun Buddhis. Akuntansi bertuhan berarti menyadari bahwa setiap angka dan laporan adalah bagian dari pertanggungjawaban moral di hadapan Yang Maha Kuasa.
Kritik Empiris atas Akuntansi yang Kehilangan Tuhan
Sejumlah kasus besar menunjukkan bagaimana akuntansi kehilangan dimensi moralnya:
— Skandal Enron (2001): perusahaan energi AS ini runtuh akibat manipulasi laporan keuangan dengan dukungan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Kasus ini menunjukkan bagaimana akuntansi dijadikan instrumen penipuan sistematis.
— Lehman Brothers (2008): sebelum krisis keuangan global, bank investasi ini menggunakan repo 105 untuk menyembunyikan utang, menyesatkan pasar, dan mempercepat keruntuhan sistem keuangan global.
— Kasus Jiwasraya (Indonesia, 2019): skandal gagal bayar asuransi negara ini memperlihatkan lemahnya tata kelola, praktik investasi berisiko tinggi, serta laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi riil.
— Kasus Garuda Indonesia (2018): laporan keuangan tahun buku 2018 menyatakan laba padahal secara substansi merugi, hingga OJK dan BEI turun tangan.
Kasus-kasus ini membuktikan bahwa tanpa fondasi nilai, akuntansi hanya menjadi “teknologi manipulasi” untuk melanggengkan kepentingan tertentu.
Perbandingan dengan Pendekatan Riset Sejenis (Novelty)
Banyak penelitian telah membahas hubungan akuntansi dengan etika, agama, atau lingkungan:
— Islamic Accounting menekankan syariah, zakat, dan keadilan distributif (Haniffa & Hudaib, 2002).
— Spiritual Accounting fokus pada dimensi kebermaknaan dan nilai moral individu (Kamla et al., 2006).
— Environmental/Sustainability Accounting fokus pada tanggung jawab lingkungan (Gray, 1992).
Namun, artikel ini menawarkan novelty dengan menyoroti konsep bertuhan sebagai indikator moral universal yang melampaui sekat agama maupun ideologi. Ia tidak hanya bicara teknis, tetapi mencoba merumuskan kriteria normatif: apakah akuntansi dijalankan sejalan dengan prinsip ketuhanan (jujur, adil, peduli sesama, dan bertanggung jawab transendental).
Implikasi Praktis
Mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam akuntansi bukan hanya wacana filosofis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam berbagai bidang:
1. Pendidikan Akuntansi
Kurikulum akuntansi perlu menekankan etika dan tanggung jawab sosial, bukan hanya standar teknis. Mahasiswa akuntansi perlu dikenalkan pada kasus nyata manipulasi laporan, sekaligus dididik dengan kesadaran moral bahwa profesinya terkait langsung dengan kepercayaan publik.
Mata kuliah Ethics in Accounting harus menjadi inti, bukan tambahan.
Studi kasus skandal keuangan dijadikan pembelajaran kritis.
Pendekatan lintas disiplin (filsafat, teologi, sosiologi) memperkaya perspektif mahasiswa.
2. Kebijakan dan Regulasi
Regulator seperti OJK, BPK, maupun IAI harus menekankan standar keterbukaan informasi yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas bagi manipulasi laporan. Akuntansi bertuhan menuntut agar regulasi tidak hanya memenuhi pasar modal, tetapi juga menjamin kepentingan masyarakat luas.
3. Audit dan Tata Kelola Perusahaan
Profesi auditor sering berada di garis depan menjaga kejujuran laporan. Namun, konflik kepentingan (misalnya antara jasa audit dan jasa konsultasi) sering mengikis independensi. Implikasi praktisnya:
Memperkuat kode etik profesi berbasis nilai moral universal.
Menata ulang sistem honorarium agar auditor tidak terikat kepentingan klien.
Mendorong whistleblowing system yang efektif dan dilindungi secara hukum.
4. Profesi Akuntan Publik dan Pemerintahan
Di sektor publik, laporan keuangan pemerintah sering memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi tetap diselimuti kasus korupsi. Ini menandakan bahwa opini teknis tidak selalu mencerminkan akuntabilitas moral. Implikasi praktisnya adalah mengintegrasikan audit kinerja berbasis nilai keadilan sosial, bukan hanya kesesuaian teknis.
5. Praktik Bisnis dan Corporate Governance
Perusahaan perlu menginternalisasi nilai bertuhan dalam tata kelola:
Mengembangkan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang jujur dan substantif.
Memastikan keterwakilan kepentingan stakeholder, bukan hanya shareholder.
Mengintegrasikan indikator etika dan spiritualitas dalam evaluasi kinerja manajemen.
6. Peran Masyarakat dan Investor
Investor dapat mendorong akuntansi bertuhan dengan mengutamakan investasi etis (ethical investing), bukan sekadar profit maksimal. Lembaga masyarakat sipil juga bisa menjadi pengawas moral atas praktik akuntansi perusahaan maupun pemerintah.
Dengan demikian, implikasi praktis dari gagasan akuntansi bertuhan adalah transformasi menyeluruh: dari ruang kelas, regulasi, profesi, hingga praktik bisnis sehari-hari.
Penutup Reflektif
Apakah akuntansi bertuhan? Jawabannya tergantung pada bagaimana profesi ini dijalankan. Secara teknis, akuntansi dapat netral; tetapi secara sosial, ia tidak pernah bebas nilai. Jika dijalankan tanpa ruh moral, akuntansi akan menjadi alat manipulasi. Namun jika dijalankan dengan kesadaran ketuhanan, ia dapat menjadi sarana pertanggungjawaban yang jujur, adil, dan membawa manfaat bagi manusia dan alam.
Artikel ini mengusulkan indikator akuntansi bertuhan—kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas transendental—sebagai ukuran moral baru. Novelty-nya terletak pada upaya menyatukan dimensi etis universal dalam kerangka akuntansi, melampaui sekat teknis maupun ideologis.
Masa depan akuntansi tidak hanya soal standar internasional, tetapi juga soal apakah profesi ini mampu menjadi jalan menuju keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan pertanggungjawaban spiritual.
Daftar Referensi
Burchell, S., Clubb, C., & Hopwood, A. (1980). The roles of accounting in organizations and society. Accounting, Organizations and Society, 5(1), 5–27.
Cooper, D., & Hopper, T. (2007). Critical theorising in management accounting research. In Handbook of Management Accounting Research. Elsevier.
Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone.
Gray, R. (1992). Accounting and environmentalism: An exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency, and sustainability. Accounting, Organizations and Society, 17(5), 399–425.
Haniffa, R., & Hudaib, M. (2002). A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting. Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal, 6(1/2), 1–71.
Hines, R. D. (1988). Financial accounting: In communicating reality, we construct reality. Accounting, Organizations and Society, 13(3), 251–261.
Hopwood, A. (1983). On trying to study accounting in the contexts in which it operates. Accounting, Organizations and Society, 8(2-3), 287–305.
Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic accounting policy perspectives. Accounting Forum, 30(3), 245–265.
Tinker, T. (1985). Paper prophets: A social critique of accounting. Praeger.
Weber, M. (2002). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge. (Original work published 1905)