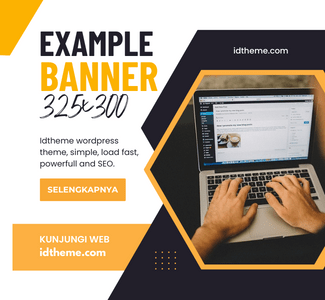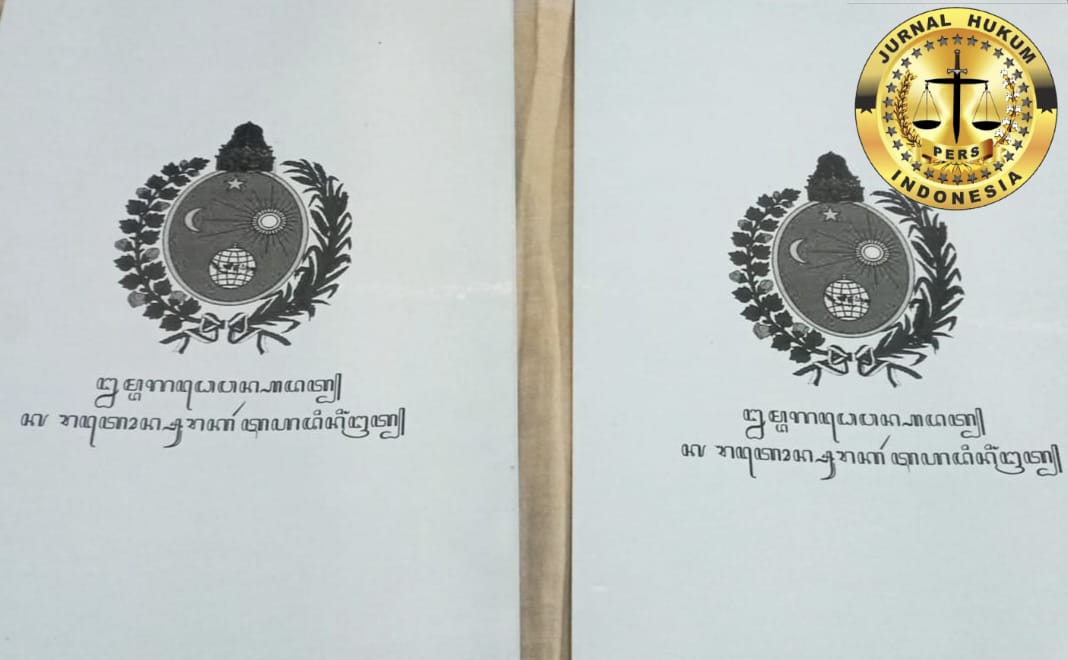Bangkalan, Jurnal Hukum Indonesia.–
11 Oktober 2025, Fenomena “Sindrom Gelar Adat” semakin ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini mengacu pada kecenderungan sebagian masyarakat untuk mengejar gelar kebangsawanan atau gelar adat bukan semata karena garis keturunan atau legitimasi adat, melainkan sebagai simbol status sosial yang dianggap mampu meningkatkan prestise pribadi maupun kelompok.
Fenomena ini muncul seiring maraknya pemberian gelar di berbagai daerah—baik melalui jalur resmi lembaga adat maupun dengan cara instan yang kerap menimbulkan polemik. Tidak jarang, gelar adat diberikan tanpa melalui prosesi adat yang sesungguhnya. Bahkan, ada yang bisa “dibeli” dengan sejumlah fasilitas, sumbangan, atau kontribusi finansial tertentu.
Gelar Adat: Simbol Kehormatan yang Sakral
Sejak masa lalu, gelar adat memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia bukan sekadar tambahan nama, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab moral, sekaligus penanda kedudukan sosial dalam struktur masyarakat tradisional.
Gelar seperti Raden, Kanjeng, Gusti, Mas, hingga berbagai gelar kebangsawanan daerah Nusantara, selalu melekat dengan legitimasi sejarah dan peran nyata bagi masyarakat.
Namun, seiring perubahan zaman, makna tersebut mulai bergeser. Gelar adat yang dahulu diperoleh karena jasa, kepemimpinan, atau garis keturunan yang jelas, kini terkadang hanya dipandang sebagai atribut prestise.
“Kalau dulu, gelar itu datang karena seseorang benar-benar mengabdi pada rakyat atau karena lahir dari garis keturunan tertentu. Sekarang, banyak yang mengejarnya karena alasan gengsi semata,” ungkap seorang budayawan Madura. “Bahkan banyak penyandangnya yang tidak memahami adat istiadat setempat.”
Fenomena Sosial: Gelar sebagai Simbol Gengsi
Bagi sebagian kalangan, gelar adat dipandang mampu membuka akses sosial yang lebih luas. Seseorang dengan gelar kebangsawanan sering kali dianggap lebih terhormat, lebih dihargai, bahkan lebih mudah diterima dalam lingkaran elite sosial.
Hal ini memunculkan apa yang disebut Sindrom Gelar Adat — di mana orang berlomba-lomba menyematkan gelar pada namanya.
Di era media sosial, tren ini semakin menguat. Banyak individu secara terang-terangan menampilkan gelar mereka di profil akun, undangan acara, hingga kartu nama. Gelar yang panjang dianggap menambah wibawa, meskipun tidak selalu dibarengi peran nyata dalam masyarakat.
“Ini sudah jadi semacam kompetisi tidak tertulis. Siapa yang punya gelar lebih banyak, dianggap lebih tinggi derajatnya. Padahal nilai sejati gelar bukan di situ,” ujar salah satu tokoh adat yang enggan disebut namanya.
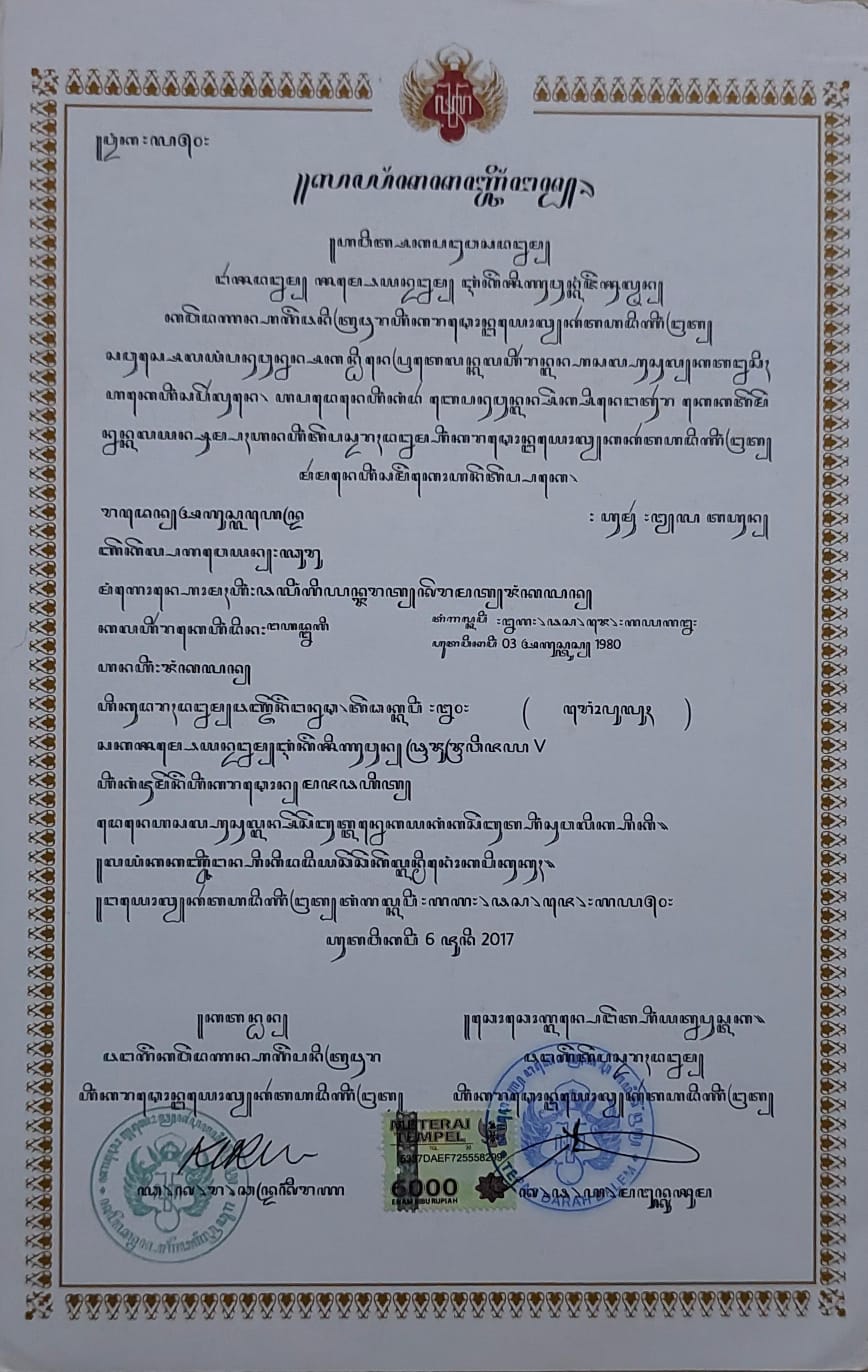
Dampak Positif dan Negatif
Fenomena Sindrom Gelar Adat sejatinya memiliki dua sisi.
Dampak positifnya, masyarakat menjadi semakin mengenal dan menghargai warisan budaya. Banyak orang kemudian tertarik mempelajari sejarah leluhur, struktur kebangsawanan, hingga sistem gelar yang berlaku di daerah masing-masing. Hal ini, pada titik tertentu, dapat memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Namun, dampak negatifnya cukup mengkhawatirkan. Jika gelar adat menjadi komoditas yang diperdagangkan, maka nilai sakral tradisi akan terdegradasi. Gelar yang seharusnya lahir dari legitimasi adat bisa kehilangan makna, dan masyarakat pun mulai meragukan otoritas lembaga adat yang memberikannya.
“Kalau gelar bisa diperjualbelikan, maka generasi muda akan melihat adat hanya sebatas formalitas, bukan warisan luhur yang harus dijaga,” kata seorang akademisi budaya.
Mengembalikan Makna Gelar Adat
Para pemerhati budaya menilai, kunci untuk mengatasi fenomena ini adalah edukasi dan pelurusan makna. Gelar adat tidak boleh dipandang sekadar sebagai hiasan nama atau alat gengsi.
Gelar harus kembali dimaknai sebagai tanggung jawab sosial, kewajiban melindungi rakyat, serta simbol pengabdian pada nilai-nilai budaya.
Masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menilai legitimasi. Penting membedakan antara gelar yang sah secara adat dengan yang hanya klaim pribadi tanpa dasar adat yang legitimate.
“Yang harus dilihat bukanlah seberapa panjang gelar seseorang, melainkan seberapa nyata kontribusinya bagi budaya, masyarakat, dan bangsa,” tegas seorang tokoh adat Madura Barat.
Refleksi Budaya
Fenomena Sindrom Gelar Adat merupakan cerminan dinamika identitas budaya di era modern.
Di satu sisi, ada kebanggaan terhadap tradisi; di sisi lain, ada godaan untuk menjadikannya alat status sosial.
Tantangan terbesar kini adalah menjaga agar warisan leluhur tidak kehilangan makna. Gelar adat harus tetap dijaga sebagai simbol luhur budaya, bukan sekadar aksesoris sosial.
Sebab, pada akhirnya, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh panjangnya gelar yang melekat di depan namanya, melainkan oleh karya dan baktinya bagi sesama.
RP. Iskandar Ahadiyat